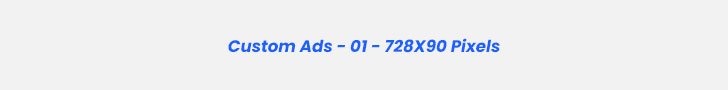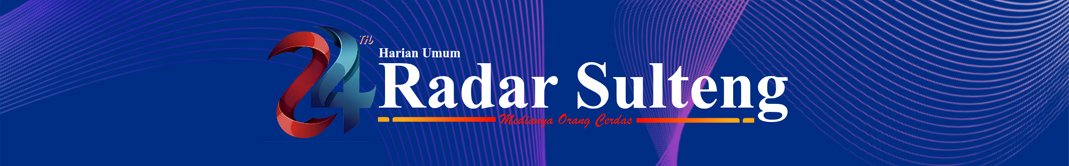Ditulis oleh :dr. Fitra Kemalasari Badrun, MH
Pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang selama bertahun-tahun dikurung di ruang gelap, dirantai di bawah kolong rumah bahkan di ikat untuk membatasi pergerakan bukan karena kejahatan melainkan karena mengidap gangguan jiwa? Realita menyakitkan ini masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, praktik ini dikenal sebagai pemasungan. Sebagian masyarakat masih melihat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai sesuatu yang memalukan, merepotkan, bahkan berbahaya. Imbasnya perilaku seperti pemasungan, pengikatan dan pengurungan masih kerap terjadi, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa.
Dalam praktik medis dan psikiatri modern, pemasungan tidak menjadi bagian dari terapi. Gangguan jiwa seperti skizofrenia, bipolar, maupun depresi berat merupakan kondisi yang dapat diobati dan dikendalikan serupa dengan penyakit diabetes atau hipertensi. Penanganan gangguan ini memerlukan pendekatan terpadu secara medis, psikologis, sosial, dan dukungan lingkungan yang konsisten. Alih-alih membantu, pemasungan justru bisa memperparah gangguan jiwa yang di alami seseorang. Saat ODGJ dikurung, mereka dapat kehilangan akses terhadap terapi, dukungan sosial dan peluang besar untuk pulih. Secara emosional, hal ini dapat menimbulkan trauma yang kompleks dan menghambat proses penyembuhan.
Pemasungan Bukan Solusi
Tentu saja tindakan pemasungan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan secara tegas dilarang dalam kerangka hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk terbebas dari tindakan pemasungan atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Pasal 494 ayat (3) UU bahkan menegaskan bahwa tindakan pemasungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak ODGJ sebagai manusia yang merdeka. Namun kenyataannya, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pemasungan masih ditemukan di berbagai daerah, meskipun tren nasional menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti stigma yang kuat dan kurangnya pemahaman masyarakat. Padahal dalam pendekatan kesehatan jiwa modern, penanganan ODGJ semestinya dilakukan dengan cara yang berbasis hak asasi manusia dengan melibatkan keluarga, komunitas, serta dukungan negara melalui sistem pelayanan terintegrasi. Tindakan perawatan secara paksa hanya dapat dilakukan sesuai prosedur medis dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui praktik pemasungan.
Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik ini. UU Kesehatan terbaru memberi ruang bagi peran lintas sektor dalam mengawal perlindungan ODGJ. Hal ini sejalan dengan pendekatan community-based mental health, yang menekankan pentingnya rehabilitasi psikiatri di tengah masyarakat, bukan di balik jeruji atau rantai. Psikiater dan tenaga kesehatan jiwa juga memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi, menjembatani antara kebutuhan medis dan pendekatan budaya, serta memastikan bahwa setiap tindakan penanganan dilakukan secara etis, manusiawi, dan sesuai hukum.Perlu ditekankan bahwa pemasungan bukanlah solusi, melainkan bentuk keputusasaan dalam menghadapi kompleksitas gangguan jiwa. Namun, dengan hadirnya regulasi baru yang lebih tegas, kita memiliki pijakan hukum yang kuat untuk menghapus praktik ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menegakkan hukum, memperluas layanan kesehatan jiwa, dan menghapus stigma di masyarakat.
Kontribusi Masyarakat
Masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam penanganan dan pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui berbagai langkah konkret. Pertama, edukasi publik sangatlah penting untuk menyebarkan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Masyarakat perlu memahami bahwa stigma terhadap ODGJ harus diubah agar pemulihan bisa terjadi tanpa diskriminasi. Kedua, deteksi dini perlu dilakukan jika ditemukan ODGJ dalam kondisi darurat, dengan segera membawa mereka ke Puskesmas atau Rumah Sakit Jiwa terdekat. Ketiga, masyarakat harus memahami bahwa praktik pemasungan merupakan tindak pidana yang bisa dan harus dilaporkan kepada pihak berwenang. Terakhir, setelah ODGJ menjalani rehabilitasi, penting bagi lingkungan sekitar untuk memberikan dukungan pascarehabilitasi, seperti membantu proses reintegrasi sosial agar mereka tidak kembali dikurung atau dikucilkan.
Pemasungan ODGJ adalah cerminan kegagalan kita sebagai masyarakat dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan UU Kesehatan 2023 sebagai panduan, saatnya kita menghentikan praktik yang tidak manusiawi ini, dan memastikan ODGJ diperlakukan sebagai manusia seutuhnya—dengan hak untuk sembuh, tumbuh, dan kembali bermakna di tengah masyarakat.