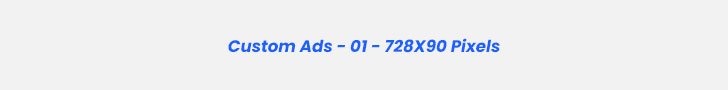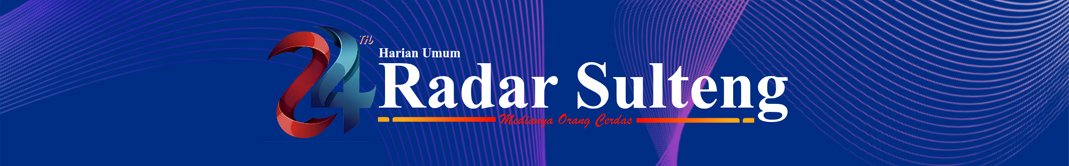Oleh: Prof. Dr. Ir. Naharuddin, S.Pd., M.Si.
(Dosen Fakultas kehutanan Universitas Tadulako dan Ketua Forum DAS Sulawesi Tengah)
Kabar68.OPINI – Di tengah gegap gempita pembangunan dan bayang-bayang krisis ekologis yang kian menekan nadi bumi, mengalir perlahan sebuah kesadaran baru dari ruang kebijakan nasional: bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) bukan sekadar perkara teknis tentang tata air, melainkan kisah agung tentang keberlanjutan peradaban manusia. Dalam paparan visioner Direktur Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan DAS di IPB University pada pertemuan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA), 1 November 2025, terlukis sebuah lanskap kebijakan yang utuh paduan antara ilmu, kebijakan, dan nurani sebuah orkestra kebumian di mana air, tanah, dan manusia berpadu menjadi simfoni keberlanjutan yang menggema dari hulu hingga hilir Nusantara.
DAS adalah entitas hidup yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan kehidupan. Dalam definisi peraturan pemerintah, ia dipandang sebagai satuan ekosistem yang menyatukan air dan tanah, dari punggung bukit hingga garis pantai. Namun, dalam kacamata yang lebih filosofis, DAS adalah cermin peradaban tempat di mana harmoni atau disharmoni antara manusia dan alam terpantul paling jujur.
Direktur PDASRH menegaskan, pengelolaan DAS harus bersifat integratif, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi. Ini bukan sekadar slogan, tetapi tuntutan sistemik terhadap pendekatan pembangunan yang selama ini sering terfragmentasi. Hulu dan hilir bukan lagi dua kutub yang berjauhan, melainkan satu aliran nilai ekologis yang saling menghidupi.
Ketika banjir berulang, tanah longsor meluas, dan mata air mengering, sesungguhnya yang runtuh bukan hanya lereng atau tanggul, melainkan tata kelola yang kehilangan arah keseimbangan. Karena itu, kebijakan pengelolaan DAS kini tidak lagi berhenti pada inventarisasi, tetapi melangkah pada rekonsiliasi antara ruang ekologis dan ruang pembangunan.
Data yang disampaikan menohok nurani: dari 2.139 bencana pada tahun 2025, lebih dari separuhnya adalah banjir dan tanah longsor. Fenomena ini bukan takdir alamiah, melainkan akibat degradasi lanskap dan lemahnya tata ruang yang mengabaikan prinsip hidrologi.
Di sinilah arah kebijakan PDASRH menjadi terapi ekologis. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 12,7 juta hektar bukan sekadar program tanam, melainkan gerakan rekonstruksi fungsi ekosistem nasional. Pendekatan berbasis lanskap (landscape approach) yang diusung membuka cakrawala baru: setiap lereng, rawa, dan dataran bukan hanya ruang ekonomi, tetapi ruang kehidupan yang harus dipulihkan secara ekologis dan sosial.
Keterlibatan masyarakat, komunitas, dan swasta menjadi jantung dari strategi ini. Kementerian tak lagi berdiri sebagai pengendali tunggal, melainkan fasilitator kolaborasi. Kebijakan ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa puisi kebumian, adalah ajakan untuk menanam harapan, bukan sekadar pohon.
Paparan Direktur PDASRH memotret dengan tajam relasi antara pangan, energi, dan air (Food EnergyWater Nexus). Di sinilah kebijakan pengelolaan DAS melampaui batas kehutanan menuju bioekonomi hijau nasional.
Lahan kritis tidak lagi dipandang sebagai beban ekologis, melainkan sebagai laboratorium peradaban tempat manusia belajar kembali tentang keseimbangan air, energi, dan kehidupan yang tumbuh dari luka bumi. Penanaman jenis bioenergi seperti nyamplung, kaliandra, dan gamal di kawasan hutan produksi menjadi simbol transisi menuju bioenergi berkeadilan energi yang tumbuh dari tanah rakyat, menggerakkan ekonomi hijau, dan mengurangi emisi.
Pendekatan ini memperlihatkan visi yang futuristik dan inklusif. Ketika dunia menatap 2050 dengan kecemasan atas krisis air dan energi, Indonesia justru menyiapkan diri dengan strategi integratif berbasis DAS di mana setiap tetes air yang tersimpan adalah investasi bagi masa depan ekonomi hijau dan kesejahteraan sosial.
Rencana rehabilitasi 10 juta hektar lahan dalam lima tahun ke depan adalah langkah raksasa yang jarang berani diambil oleh negara berkembang. Angka-angka yang disajikan 72,8 triliun rupiah dari APBN dan 130 triliun dari non APBN bukan sekadar statistik, melainkan tanda keseriusan sebuah bangsa untuk berdamai dengan alamnya.
Lebih dari itu, program RHL menjadi wujud diplomasi kehidupan (ecological diplomacy): antara pemerintah dan rakyat, antara generasi kini dan yang akan datang. Di balik setiap hektar lahan yang direhabilitasi, tersimpan nilai moral bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang memperpanjang umur bumi.
Pendekatan vegetatif dan sipil teknis yang digandengkan dengan pemulihan mangrove, imbuhan mata air, serta pengelolaan sumber benih menunjukkan paradigma baru: bahwa konservasi adalah kerja ilmiah sekaligus kerja cinta.
Visi Presiden tentang Swasembada Air menemukan pijakan konkret dalam kebijakan PDASRH. Pemulihan 5.000 mata air kritis menjadi simbol kebangkitan hidrologi nasional. Air bukan lagi sekadar sumber daya, tetapi sumber daya kehidupan yang menjadi dasar kedaulatan bangsa.
Air, dalam perspektif ekosistem DAS, adalah teks yang ditulis oleh hutan, dibaca oleh tanah, dan dihafalkan oleh masyarakat. Maka, ketika air berhenti mengalir, itu tanda bahwa kita lupa membaca doa paling purba dari bumi.
Kebijakan ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tanpa air adalah kesombongan, dan air tanpa kehutanan adalah kehilangan akar. Rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan terpadu menjadi trilogi kebijakan yang saling menopang untuk memastikan Indonesia tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh secara ekologis.
Di penghujung paparan, kalimat “DAS Sehat, Indonesia Kuat” bergema bukan sebagai slogan, melainkan ikrar peradaban. Bahwa pengelolaan DAS bukan semata kerja teknokratik, melainkan laku spiritual bangsa untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi.
Ketika kebijakan bersentuhan dengan nurani, dan strategi berpijak pada ilmu pengetahuan, maka yang lahir bukan hanya dokumen, tetapi gerakan moral nasional. Gerakan untuk menyehatkan sungai, menegakkan hutan, dan memulihkan martabat manusia sebagai bagian dari ekosistem.
Kita belajar dari air ia selalu mengalir ke tempat rendah, namun justru dari situlah kehidupan bermula. Seperti kebijakan PDASRH yang mengalir lembut namun menyuburkan, membawa pesan bahwa peradaban sejati bukan dibangun di atas dominasi manusia terhadap alam, tetapi atas harmoni keduanya.
(Opini ini didedikasikan untuk refleksi atas paparan Direktur PDASRH Kementerian Kehutanan Republik Indonesia)