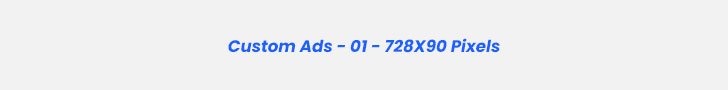Oleh : Naharuddin S.H., M.H
PROLOG
Salah satu masalah besar yang terus menghantui partai politik (parpol) di Indonesia adalah rapuhnya soliditas internal akibat konflik perebutan posisi ketua umum. Dalam sistem demokrasi, suksesi kepemimpinan semestinya menjadi momen regenerasi dan konsolidasi organisasi. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya, suksesi berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang berujung pada perpecahan.
Dualisme kepengurusan partai pasca suksesi kini menjadi fenomena berulang yang melemahkan fungsi dan kemandirian parpol. Konflik kepemimpinan sering kali menimbulkan dua kubu yang sama-sama mengklaim legalitas, masing-masing merasa paling sah dan mewakili partai. Situasi ini bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hingga memasuki tahapan pemilu, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian elektoral yang serius.
Fakta menunjukkan bahwa beberapa partai politik yang sempat memiliki kursi di DPR RI, dalam Pemilu 2014, 2019, hingga 2024, akhirnya harus tersingkir karena gagal memenuhi parliamentary threshold. Akar persoalannya bukan pada ideologi, bukan pada program, tetapi pada disintegrasi internal. Ketika energi partai habis untuk bertikai, tidak ada lagi waktu dan tenaga untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Di sinilah krisis partai politik Indonesia sesungguhnya berakar.
PARPOL MUDAH DIADU DOMBA
Jika ditelusuri sepanjang perjalanan pemilu antara tahun 2015 hingga 2024, konflik perebutan ketua umum di sejumlah partai sering kali bukan murni persoalan internal, melainkan merupakan proyek politik yang disponsori pihak eksternal. Intervensi semacam ini kerap terjadi terutama terhadap partai yang ketua umumnya tidak berada dalam orbit kekuasaan, atau mengambil posisi politik yang berseberangan dengan pemerintah.
Dalam banyak kasus, usaha menjatuhkan ketua umum dilakukan melalui berbagai cara. Ada yang menggunakan jalur formal dengan memanfaatkan mekanisme kongres, munas, atau musyawarah luar biasa, namun tidak sedikit pula yang ditempuh melalui cara kudeta politik yang bersifat ilegal. Cara-cara demikian menunjukkan betapa lemahnya daya tahan internal partai terhadap intervensi eksternal.
Kita bisa menengok kembali pengalaman Partai Golkar pada tahun 2015, yang terbelah akibat pertarungan dua kubu kepengurusan. Hal yang sama juga dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura, bahkan Partai Demokrat sempat mengalami upaya kudeta internal yang diduga kuat disponsori kekuatan politik dari luar. Semua ini menunjukkan satu hal penting: parpol kita masih sangat mudah diadu domba.
Mengapa kondisi ini bisa terjadi? Penyebab utamanya terletak pada desain kelembagaan yang menempatkan legalitas kepengurusan parpol di bawah kewenangan eksekutif.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, kepengurusan partai yang diakui sah oleh negara untuk kepentingan kepesertaan pemilu, pencalonan legislatif, presiden, hingga kepala daerah, adalah kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan desain seperti ini, posisi partai politik menjadi sangat tergantung pada kekuasaan eksekutif. Pemerintah dapat dengan mudah memainkan legitimasi kepengurusan, cukup dengan “menciptakan” konflik internal, lalu mendorong pelaksanaan munaslub atau kongres luar biasa. Setelah salah satu hasil kongres tersebut disahkan oleh pemerintah, maka otomatis satu kubu menjadi “resmi”, sementara kubu lain tersingkir secara hukum. Inilah titik paling rentan yang menjadikan partai politik di Indonesia tidak mandiri dan rawan diintervensi.
Ketika kemandirian partai hilang, fungsi parpol sebagai pilar demokrasi berubah menjadi instrumen kekuasaan. Parpol tidak lagi berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan rakyat, tetapi menjadi perpanjangan tangan kepentingan rezim. Demokrasi pun kehilangan makna substantifnya, karena partai politik sebagai jantung demokrasi justru tidak berdaulat atas dirinya sendiri.
MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI POLITIK
Undang-Undang tentang Partai Politik sebenarnya telah menyiapkan perangkat hukum untuk penyelesaian konflik internal parpol. Dalam regulasi disebutkan bahwa sengketa kepartaian dapat diselesaikan melalui dua jalur utama:Mahkamah Partai, dan Gugatan ke pengadilan negeri.
Mahkamah Partai merupakan forum internal yang diberi kewenangan untuk memutus sengketa yang terjadi antarpengurus atau anggota partai. Namun, dalam praktiknya, lembaga ini sering kali tidak berjalan efektif karena mahasiswa partai cenderung berpihak pada salah satu kubu. Objektivitasnya diragukan, apalagi ketika konflik sudah melibatkan kepentingan elite pusat.
Jika penyelesaian di Mahkamah Partai buntu, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun jalur ini pun tidak selalu memberikan solusi yang cepat dan tuntas. Putusan pengadilan sering kali baru keluar setelah momentum politik berlalu. Akibatnya, penyelesaian hukum justru tidak mampu mengembalikan keutuhan partai secara sosial dan politis.
Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga kesadaran kolektif untuk melakukan rekonsiliasi internal. Partai politik harus kembali pada nilai dasar pendiriannya: membangun demokrasi, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan menjadi wadah politik yang beretika. Tanpa kesadaran ini, setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan, maka dualisme akan terus berulang.
Karena itu, reformasi sistem kepartaian perlu diarahkan pada penguatan kemandirian internal partai. Pemerintah sebaiknya tidak lagi memiliki kewenangan absolut dalam mengesahkan kepengurusan. Legalitas partai idealnya dikembalikan pada keputusan internal organisasi yang sah dan demokratis. Dengan demikian, partai tidak lagi menjadi “sandang kuasa”, melainkan menjadi institusi politik yang otonom dan bermartabat.
EPILOG
Dualisme kepengurusan partai politik adalah gejala penyakit kronis demokrasi kita. Ia lahir dari kombinasi antara ambisi kekuasaan, lemahnya etika politik, dan intervensi eksternal. Sementara, rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru menjadi korban karena kehilangan alternatif politik yang kredibel.
Jika partai politik ingin tetap eksis dan dipercaya, maka soliditas, moralitas, dan kemandirian harus dikembalikan sebagai fondasi utama. Tanpa itu, partai hanya akan menjadi rumah yang mudah dirobohkan oleh angin kekuasaan.
Tentang Penulis : Naharuddin S.H., M.H adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako