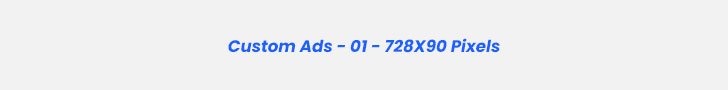oleh: Ridaya Laodengkowe
(Geograf, Pemerhati Kebijakan Publik, pau Banggai)
Kabar68 – Beberapa waktu terakhir jagat medsos dihebohkan oleh “drama kecil” soal Danau Paisupok—ikon wisata cantik berair biru toska di Banggai Kepulauan. Keributannya sepele tapi serius: ada akun promosi wisata yang keliru menyebut lokasi danau itu di Kabupaten Banggai, bukan Banggai Kepulauan.
Kesalahan ini langsung menyulut protes. Warga Bangkep merasa identitas daerahnya dicaplok, sementara sebagian orang di luar menganggapnya sekadar salah tulis. Perdebatan pun melebar, ada yang menegaskan ini soal branding dan kebanggaan, ada pula yang menyepelekan.
Kalau ditelisik, keributan Paisupok ini bukan hal baru. Ia adalah gejala persoalan lebih besar: kerancuan nama wilayah di tiga kabupaten bersaudara—Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Nama yang mirip sering bikin bingung, apalagi bagi orang luar daerah. Padahal bagi warga setempat, membedakannya sangat mudah, bahkan kalau ditanya di tengah malam sekalipun.
Sejarah Pemekaran Tiga Banggai
Tiga daerah ini punya tautan kesejarahan dan kekerabatan panjang, tak terpisahkan secara historis, kultural, sosial, dan ekonomi. Semula semua berada dalam Kabupaten Banggai beribukota Luwuk (UU No 29/1959). Lalu dimekarkan dua kali: tahun 1999 lahirlah Kabupaten Banggai Kepulauan (UU No 51/1999), dan tahun 2013 Kabupaten Banggai Laut (UU No 5/2013).
Bagi warga lokal, membedakan ketiganya mudah. Tapi bagi banyak orang luar, bahkan pejabat provinsi dan kementerian, sering kali membingungkan. Saya berkali-kali menjumpai pejabat di Jakarta yang keliru ketika bicara soal “Banggai”, padahal mereka mengurus alokasi anggaran atau kebijakan. Kesalahan semacam ini jelas berisiko salah sasaran.
Para akademisi dan peneliti pun kerap mengalami hal serupa. Pelaku usaha dan penyedia jasa, apalagi. Butuh waktu lama hanya untuk memastikan: Banggai yang dimaksud ini Banggai daratan, Bangkep (Pulau Peling), atau Banggai Laut (Balut)?
Gejala Akut: Bingung Geografi, Ingat Duit
Fenomena ini ironis, mencerminkan penyakit akut kita: kurang akrab dengan geografi dan sejarah, tapi cepat hafal kalau urusannya uang. Tidak heran kalau salah alamat sering terjadi. Promosi wisata salah sasaran, branding produk lokal meleset, hingga potensi besar dari indikasi geografis (geographical indication) untuk produk-produk khas bisa terganggu.
Bayangkan jika promosi besar-besaran dilakukan pemerintah daerah untuk menarik wisatawan, tapi publik salah paham dan justru berkunjung ke kabupaten tetangga. Atau, kalau identifikasi geografis untuk spesies endemik dan produk unggulan meleset, padahal nilainya tinggi. Kerugian bisa nyata, bukan sekadar salah tulis.
Celah untuk Perubahan
Karena itu, barangkali sudah waktunya kita memikirkan ulang toponimi (nama daerah) tiga kabupaten ini. Perubahan nama daerah bukan mustahil. Ada jalur hukum jelas dalam UU Pemerintahan Daerah (UU No 23/2014): usulan pemerintah daerah, rekomendasi gubernur, diteruskan ke pusat, dan diputuskan melalui Peraturan Pemerintah. Proses ini bahkan lebih sederhana daripada pemekaran atau perubahan batas wilayah.
Pengalaman Indonesia cukup banyak: Kabupaten Klungkung mengubah nama ibukotanya jadi Semarapura (PP No 18/1992), Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe (PP 59/2014), Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kepulauan Tanimbar (PP No 2/2019), dan Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba (PP No 14/2020).
Ada pula perubahan lain, misalnya Kotamadya Ujung Pandang yang kembali memakai nama Makassar (UU No 9/1995), atau penghilangan kata “Induk” pada daerah pasca pemekaran—seperti Ogan Komering Ulu (UU No 37/2003) dan Bolaang Mongondow (UU No 10/2007).
Alasannya tidak selalu rumit—kadang deskriptif saja, atau menegaskan identitas lokal yang lebih dikenal. Intinya: ada kebutuhan praktis yang dirasakan.
Opsi untuk Tiga Banggai
Untuk konteks toponimi Banggai bersaudara, saya ajukan satu opsi provokatif tapi realistis:
- Kabupaten Banggai → Kabupaten Babasal
Babasal adalah akronim Banggai, Balantak, Saluan—tiga etnis asli di wilayah ini. Dalam bahasa Banggai, babasal juga berarti “besar”, seperti Paisu Babasal (kuala besar) atau Bonua Babasal (rumah besar). Nama ini bukan hanya akurat, tapi simbolik: Banggai daratan tetap jadi rumah bersama.
Kita punya preseden sukses: Kabupaten Wakatobi, akronim dari Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Bukan saja diterima masyarakat, Wakatobi bahkan dikenal luas di tingkat nasional dan internasional sebagai destinasi wisata unggulan. Artinya, akronim bisa sah, bermakna, dan efektif menjadi identitas resmi.
- Kabupaten Banggai Kepulauan → Kabupaten Peling
Faktanya, 98 persen wilayah Banggai Kepulauan ada di satu pulau besar, Pulau Peling (atau Peleng). Dalam percakapan sehari-hari pun orang sudah terbiasa menyebut “di Peling” untuk menyebut daerah ini. Jadi, alih-alih “kepulauan” yang menyesatkan, nama Peling jauh lebih deskriptif, netral, sekaligus akrab. - Kabupaten Banggai Laut → Kabupaten Kepulauan Banggai
Wilayah ini justru paling absah memakai identitas “kepulauan” dan “Banggai”. Ada belasan pulau berpenghuni dan ratusan pulau kecil tempat orang mencari nafkah. Pusat Kerajaan Banggai dulu juga di sini. Menyebutnya “Kepulauan Banggai” lebih pas (deskriptif), dan lebih mudah diterjemahkan ke bahasa asing ketimbang “Banggai Laut”.
Penutup: Dari Paisupok ke Masa Depan
Perubahan nama geografis tiga kabupaten ini hanya bermakna jika dilakukan bersama-sama. Kalau hanya satu atau dua yang berganti, kebingungan baru bisa muncul. Idealnya ada satu paket usulan dan satu nomor PP yang mengikat ketiganya. Itu akan jadi simbol kuat bahwa tiga Banggai tetap bersaudara meskipun berstatus kabupaten berbeda.
Kasus Paisupok memberi pengingatan sederhana tapi jelas sekali: persoalan nama daerah bukan hal remeh. Ia bisa memicu keributan, salah paham, bahkan salah kebijakan. Kalau tidak segera diurai, kerancuan akan terus berulang. Karena itu, mari jadikan momentum kecil dari kisah Paisupok ini sebagai pintu masuk untuk diskusi lebih besar: bagaimana menata toponimi agar lebih jelas, adil, dan membanggakan.
Kasus Paisupok ini memberi pesan sederhana: nama daerah bukan sekadar tanda, tapi bisa menimbulkan salah paham dan bahkan salah kebijakan. Pertanyaannya, bisakah kita menemukan jalan keluar agar tiga kabupaten bersaudara ini lebih jelas identitasnya, tanpa mengorbankan ikatan kultural yang lama? Besok saya akan menawarkan satu gagasan konkret untuk menjawab kerancuan ini. **